
Tata Kelola Ruang Laut Indonesia Pasca-UU Cipta Kerja: Analisis Komprehensif Implementasi, Tantangan, dan Proyeksi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)
Artikel ini mengupas tuntas konteks strategis penataan ruang laut, anatomi regulasi KKPRL, mekanisme implementasi melalui OSS-RBA, tantangan multidimensi di lapangan, studi kasus “pagar laut” Tangerang, perbandingan KKPRL vs KKPR, hingga rekomendasi kebijakan ke depan.
Bagian 1: Menegaskan Kedaulatan di Laut: Konteks Strategis Penataan Ruang Laut Indonesia
1.1. Dari Deklarasi Djuanda ke Poros Maritim Dunia: Evolusi Konsepsi Ruang Laut Nasional
Sejarah konsepsi ruang laut Indonesia modern berakar pada Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957). Deklarasi ini mengubah status perairan di antara ribuan pulau—yang sebelumnya dianggap laut bebas—menjadi perairan pedalaman di bawah kedaulatan NKRI. Perjuangan diplomasi selama lebih dari 25 tahun untuk mendapatkan pengakuan konsep archipelagic state berbuah melalui UNCLOS 1982, yang memberikan landasan yuridis internasional kokoh bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Meski demikian, paradigma pembangunan di masa lalu cenderung “memunggungi laut”. Degradasi ekosistem pesisir dan pelanggaran kedaulatan maritim merebak. Menjawab itu, visi Poros Maritim Dunia dicanangkan—ditopang lima pilar: (1) membangun budaya maritim; (2) menjaga & mengelola sumber daya laut; (3) infrastruktur & konektivitas maritim; (4) diplomasi maritim; (5) pertahanan maritim.
Dalam kerangka ini, penataan ruang laut menjadi instrumen strategis krusial. Tanpa perencanaan spasial yang teratur, terintegrasi, dan berkelanjutan, pemanfaatan masif akan menimbulkan konflik dan mengancam kedaulatan.
1.2. Ekonomi Biru sebagai Paradigma Pembangunan: Menyeimbangkan Konservasi dan Pertumbuhan
Ekonomi Biru diadopsi sebagai kerangka pembangunan kelautan: sistem ekonomi berkelanjutan berlandaskan prinsip ekologi untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan, dan meminimalkan dampak lingkungan. Konsep ini berbeda dari Blue Growth (berfokus pertumbuhan ekonomi) dan Sustainable Ocean Economy (memprioritaskan kesehatan ekosistem).
Marine spatial planning menjadi prasyarat mutlak. Tanpa alokasi ruang yang jelas, konflik antar-sektor (perikanan, budidaya, pariwisata, migas, pelayaran, konservasi) akan meningkat dan mengancam pilar keberlanjutan ekologi.
KKP mendorong Ekonomi Biru melalui lima program prioritas: (1) perluasan kawasan konservasi; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota; (3) budidaya ramah lingkungan; (4) pengelolaan pesisir & pulau kecil berkelanjutan; (5) pengurangan sampah laut. Instrumen perizinan KKPRL memastikan setiap kegiatan sejalan dengan program-program ini.
1.3. Peran Sentral Penataan Ruang Laut dalam Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi dan Ekologi
Ada hierarki ketergantungan: visi Poros Maritim Dunia → strategi Ekonomi Biru → efektivitas penataan ruang laut (KKPRL). Gagal di level implementasi & pengendalian perizinan akan menimbulkan efek domino ke atas.
Integrasi tata ruang darat–laut adalah kunci. Aktivitas darat seperti industri pesisir atau pengelolaan DAS memengaruhi laut (pencemaran/sedimentasi). Penataan ruang laut menghadapi lima isu strategis: (1) pulau kecil & perubahan iklim; (2) degradasi kawasan pesisir; (3) optimalisasi yurisdiksi laut yang luas; (4) implementasi program Ekonomi Biru; (5) penataan alur kabel & pipa bawah laut yang kian padat.
Bagian 2: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL): Landasan Hukum dan Kerangka Kerja Perizinan
2.1. Anatomi Regulasi: Membedah PP No. 21/2021 dan Permen KP No. 28/2021
UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi titik balik penataan ruang, termasuk di laut. PP No. 21/2021 merombak perizinan pemanfaatan ruang: memperkenalkan KKPR menggantikan izin lokasi. PP juga mengamanatkan integrasi muatan tata ruang darat–laut dalam satu RTR.
Turunan teknisnya di sektor kelautan adalah Permen KP No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut—mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan. Permen ini mencabut regulasi menteri sebelumnya yang terpisah (izin lokasi, reklamasi, zonasi).
Dalam kerangka baru, KKPRL adalah izin dasar sebelum memanfaatkan ruang laut, terdiri dari:
- PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) untuk kegiatan berusaha/non-berusaha yang memerlukan analisis mendalam.
- KKRL (Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut) sebagai persetujuan sederhana untuk kegiatan non-berusaha tertentu yang lokasinya sudah sesuai RZ.
2.2. Fungsi KKPRL: Instrumen Pengendalian, Kepastian Hukum, dan Pencegahan Konflik
- Pengendalian pemanfaatan ruang laut agar sesuai alokasi RTR/RZ dan daya dukung lingkungan.
- Kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor melalui izin dasar tunggal.
- Pencegahan konflik multi-pengguna lewat alokasi ruang yang jelas dan partisipatif.
2.3. Kegiatan yang Wajib Memiliki KKPRL dan Pengecualiannya
Hampir semua kegiatan menetap di laut wajib KKPRL: energi & sumber daya mineral (migas), kabel/pipa bawah laut, dermaga/terminal/offshore, pengerukan/reklamasi, budidaya menetap (KJA/mutiara). Nelayan kecil/tradisional yang menangkap ikan di wilayah tangkap tradisionalnya tidak wajib KKPRL—dan harus dilindungi aksesnya.
Bagian 3: Mekanisme Implementasi: Alur Pengajuan dan Penilaian Teknis KKPRL melalui Sistem OSS
3.1. Integrasi Perizinan: Peran OSS-RBA
Untuk kegiatan berusaha, KKPRL terintegrasi dengan OSS-RBA sebagai single gateway. Tujuan: cepat, transparan, terstandar, bebas pungli. Kegiatan non-berusaha diajukan via sistem elektronik KKP.
3.2. Tahapan Pengajuan: Dari Pendaftaran hingga Penerbitan
- Pendaftaran & Data Usaha: akun OSS, pilih KBLI, lengkapi data.
- Unggah Dokumen Teknis (krusial): rencana kegiatan; peta lokasi + koordinat; pemanfaatan ruang sekitar; data kondisi terkini (ekosistem, hidro-oseanografi, batimetri, sosial-ekonomi); khusus reklamasi: sumber material, rencana pemanfaatan, jadwal.
- Verifikasi & Penilaian KKP: cek kelengkapan & validitas; jika kurang dikembalikan.
- PNBP: jika layak & dikenakan biaya, terbit SPS; bayar & unggah bukti.
- Penerbitan PKKPRL: setelah verifikasi pembayaran & penilaian substantif; target selesai 20 hari sejak pembayaran terverifikasi.
| No. | Tahapan Proses | Pelaku | Dokumen/Output | Platform | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran Akun & Pengisian Data | Pelaku Usaha | Akun OSS, NIB | OSS-RBA | Waktu tergantung kelengkapan |
| 2 | Pengajuan Permohonan PKKPRL | Pelaku Usaha | Form PKKPRL | OSS-RBA | - |
| 3 | Unggah Dokumen Teknis | Pelaku Usaha | Peta, Koordinat, Data Lingkungan, dsb. | OSS-RBA | Menentukan kecepatan proses |
| 4 | Verifikasi Kelengkapan | Verifikator KKP | Notifikasi (lengkap/perbaikan) | OSS-RBA | ±1–3 hari kerja |
| 5 | Penilaian Substantif Awal | Tim Penilai KKP | Catatan kelayakan | Internal KKP | Bagian dari 14 hari kerja pertama |
| 6 | Penerbitan SPS PNBP | Verifikator KKP | SPS (kode billing) | OSS-RBA | Jika permohonan layak |
| 7 | Pembayaran PNBP | Pelaku Usaha | Bukti pembayaran | Bank/Sistem Pembayaran | Sesuai SPS |
| 8 | Verifikasi Pembayaran | Sistem & Verifikator | Notifikasi terverifikasi | OSS-RBA | ±1–2 hari kerja |
| 9 | Penilaian Substantif Akhir | Tim Penilai & Admin KKP | Draf PKKPRL | Internal KKP | Bagian dari 6 hari kerja sisa |
| 10 | Penerbitan PKKPRL | Admin KKP | PKKPRL elektronik | OSS-RBA | Target 20 hari sejak pembayaran terverifikasi |
3.3. Proses Penilaian Teknis di KKP
Penilaian substantif mempertimbangkan: kesesuaian RTRL/RZ KAW/RZ KSNT/RZWP3K; daya dukung & tampung lingkungan; dampak sosial-ekologis; ekosistem penting; kepentingan strategis nasional (hankam); hak & akses nelayan; serta freedom to lay pipa/kabel sesuai hukum internasional. KKPRL adalah hasil analisis multi-kriteria, bukan formalitas.
Bagian 4: Tantangan Multidimensi dalam Implementasi KKPRL
4.1. Tantangan Teknis: Data Spasial, Interoperabilitas, & RZWP3K
Ketersediaan/kualitas data spasial & tematik laut belum memadai; integrasi OSS–basis data KKP/daerah kurang optimal; format/metadata/protokol berbeda-beda; banyak RZWP3K usang/belum disahkan. Semua ini meningkatkan risiko kesalahan & konflik.
4.2. Tantangan Administratif & Kelembagaan: Pusat–Daerah
Sentralisasi kewenangan meningkatkan efisiensi, namun berpotensi gesekan dengan daerah (disharmoni regulasi, peran daerah tereduksi). Minim pelibatan local knowledge memicu resistensi & ketidakpastian.
4.3. Tantangan Sosial-Ekonomi: Literasi Regulasi & Potensi Marginalisasi
Literasi KKPRL masyarakat pesisir/nak kecil rendah; proses digital kompleks. Peran penyuluh vital namun tantangan jangkauan besar. Risiko marginalisasi kelompok rentan meningkat jika konsultasi publik tak bermakna.
Bagian 5: Studi Kasus—Insiden “Pagar Laut” Tangerang
5.1. Kronologi & Skala Pelanggaran
Awal 2025, ditemukan “pagar laut” bambu sepanjang ±30,16 km di pesisir Kab. Tangerang. Mengkavling perairan layaknya empang. Dugaan menuju reklamasi ilegal. Dampak: akses nelayan terhalang, biaya operasi naik, kerusakan alat tangkap.
Pemerintah menindak: penyegelan, perintah bongkar, denda administratif hingga Rp 48 miliar pada pihak terlibat. Kasus memicu gugatan warga—menunjukkan kompleksitas aktor.
5.2. Analisis Yuridis
Pelanggaran berlapis: tidak memiliki KKPRL; melanggar UU 27/2007 jo. UU 1/2014 soal akses publik; potensi pelanggaran lingkungan (sedimentasi, habitat rusak); serta kejanggalan HGB di wilayah perairan—bertentangan dengan asas laut sebagai public domain.
5.3. Pelajaran
Kegagalan deteksi dini & pengawasan proaktif. Regulasi tanpa pengawasan & penegakan tegas hanyalah “macan kertas”. Diperlukan sistem monitoring aktif dan law enforcement tanpa pandang bulu.
Bagian 6: Analisis Komparatif—Kompleksitas KKPRL (Laut) vs. KKPR (Darat)
6.1. Perbedaan Fundamental: Dinamis 3D vs. Statis
Laut: dinamis (arus, pasang, gelombang), tiga dimensi (permukaan–kolom air–dasar laut). Dampak menyebar luas. Darat: relatif statis, dua dimensi, dampak lebih lokal.
6.2. Aspek Penilaian: Hak Pemanfaatan Ruang vs. Hak Atas Tanah
Di darat, KKPR terkait bukti penguasaan/sertifikat tanah. Di laut tak ada kepemilikan privat; yang ada hak pemanfaatan ruang publik untuk jangka waktu tertentu. Penilaian KKPRL menengahi multi-use space bertumpuk di satu kolom perairan.
6.3. Implikasi Perizinan & Pengawasan
Data persyaratan KKPRL jauh lebih spesifik (oseanografi, batimetri, ekologi, sosial-ekonomi). Kebutuhan SDM ahli (oseanografi, bio-kelautan, hukum laut) tinggi. Pengawasan laut: mahal, sulit, butuh satelit, drone, VMS.
| Atribut | KKPRL (Laut) | KKPR (Darat) |
|---|---|---|
| Objek Regulasi | Ruang perairan dinamis & terhubung | Bidang tanah statis & berbatas jelas |
| Dimensi Ruang | 3D (permukaan, kolom air, dasar laut) | 2D (permukaan tanah) |
| Sifat Ruang | Dinamis (arus, pasang, migrasi biota) | Statis & relatif permanen |
| Konsep Hak | Hak Pemanfaatan Ruang Publik | Hak Atas Tanah |
| Keragaman Pengguna | Sangat tinggi & tumpang tindih | Cenderung eksklusif per zona |
| Ketersediaan Data | Terbatas & mahal (oseanografi, batimetri) | Relatif lengkap & mudah diakses |
| Kompleksitas Dampak | Tinggi; dampak bisa menyebar luas | Sedang; cenderung terlokalisir |
| Tantangan Pengawasan | Sangat tinggi (luas, akses, biaya) | Sedang–tinggi (akses lebih mudah) |
Bagian 7: Menuju Tata Kelola Laut yang Berkelanjutan—Sintesis, Proyeksi, & Rekomendasi Kebijakan
7.1. Sintesis Temuan Kunci
Desain regulasi (PP 21/2021 & Permen KP 28/2021) + OSS-RBA menyiapkan kerangka canggih untuk efisiensi, kepastian, & pengendalian. Namun, ada kesenjangan antara desain ideal & realitas implementasi: fondasi data lemah, disharmoni kelembagaan, kesenjangan kapasitas, literasi rendah. Kasus pagar laut jadi alarm bahwa tanpa pengawasan/penegakan, regulasi tak bermakna.
7.2. Proyeksi Masa Depan
Skenario optimis: KKPRL jadi pilar Ekonomi Biru; perizinan berbasis data yang cepat & transparan menarik investasi berkelanjutan; konflik turun.
Skenario pesimis: tanpa perbaikan, KKPRL menjadi macan kertas; ketidakpastian tinggi; konflik sosial-ekologis berulang.
7.3. Rekomendasi Strategis
- Fondasi Data: percepat pemutakhiran & digitalisasi RZWP3K; standar data spasial nasional; portal berbagi data laut terintegrasi pusat–daerah.
- Harmonisasi Kelembagaan: bentuk forum penataan ruang laut nasional/daerah sebagai wadah koordinasi & mediasi.
- Kapasitas & Partisipasi: anggaran pelatihan teknis masif (SIG, analisis kelautan); berdayakan penyuluh perikanan dengan modul KKPRL & materi sosialisasi mudah dipahami.
- Pengawasan Teknologi: sistem monitoring proaktif berbasis satelit, drone, VMS, dan pelibatan masyarakat.
- Kebijakan PNBP: evaluasi struktur tarif agar efektif sebagai instrumen pengendalian tanpa menghambat UMKM pesisir.
Daftar Referensi (ringkas)
- PP No. 21 Tahun 2021 & Permen KP No. 28 Tahun 2021
- OSS-RBA (persyaratan dasar & alur perizinan)
- Sumber berita/studi: KKP, Kompas, Tirto, Metrotvnews, Warta Ekonomi, dsb.
Butuh pendampingan teknis penyusunan dokumen KKPRL (peta, koordinat, data oseanografi, dsb.)? Konsultasi via WhatsApp: +62 857 7374 5006.
No comments yet.


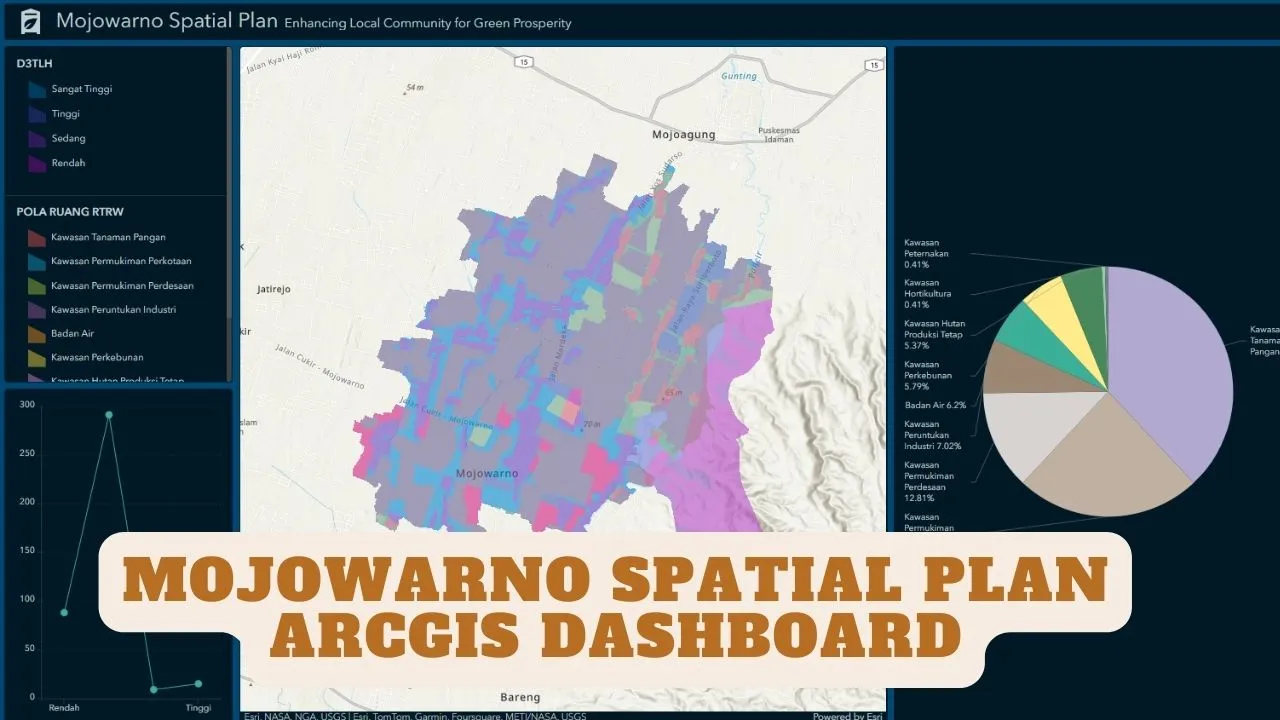
No comments yet.